Mimin yakin, masih ada pembaca yang masih bingung dengan istilah Cina, China, Tionghoa dan Tiongkok, yang berseliweran di berbagai media nasional, baik cetak, online, maupun Tv.
Tahukah pembaca, bahwa istilah “Cina” sendiri sebenarnya berkonotasi negatif di masyarakat? Laiknya sebutan “Inlander” oleh orang2 Belanda pada masa kolonial? Dimana artinya barupa ejekan, seperti pesakitan, lemah, kurus, kotor, budak, buruh, berpendidikan rendah, dan sebagainya.
Lantas mana penyebutan yang TEPAT? Dimana kita harus menggunakan istilah penyebutan2 tersebut?
Istilah2 diatas memang hanya ada di Indonesia saja. Karena untuk “versi internasionalnya” saja, hanya mengenal kata “China” (dibaca : Chaina) yang merujuk pada nama Negara, dan kata “Chinese” merujuk pada bahasa, budaya, atau orang2 nya.
Menurut catatan sejarah bangsa ini, pada pemerintahan era Orde Baru, tepatnya di tahun 1967, Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967, yang membuat adanya perubahan penyebutan kata “Tiongkok” dan “Tionghoa” menjadi kata “Cina” saja.
Istilah ini kelak akan menjadi rancu, karena tidak lagi membedakan mana penyebutan untuk nama Negaranya (Cina), dan mana penyebutan untuk orang2 keturunannya (hanya ditambah kata “keturunan” didepannya).
Jadi di masa itu, orang2 pribumi akan menyebut : “Si A orang Cina”, yang berarti “Si A keturunan Cina”, terlepas dari apakah si A berstatus WNI atau tidak (sudah lahir di Indonesia, atau sudah mengganti kewarganegaraan”.
Seiring berjalanannya waktu, sebutan “Cina” di era Orde Baru selama 3 dekade (1967-1998) menimbulkan diskriminasi terhadap masyarakat keturunan Cina di Indonesia, yang mencapai titik puncaknya pada peristiwa Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta.
Baca juga : Kerusuhan Mei 1998 : Inilah Harga yang Harus Dibayar, Sketsa Pergulatan Etnis Tionghoa di Indonesia!
Sebelum akhirnya di tahun 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Keppres No. 12 tahun 2014, yang isinya tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967 diatas.
Inti dari keppres ini adalah kata “Tiongkok” dan “Tionghoa” resmi dipakai kembali, dimana kata “Tiongkok” akan merujuk pada nama Negaranya (China), dan kata “Tionghoa” merujuk pada orang2 nya dan budayanya.
Baca juga : Presiden SBY Ganti Istilah Cina dengan Tionghoa (2014)
A. Perbedaan Istilah Cina, China, Tionghoa, dan Tiongkok
1. Kata “Cina” merupakan penyebutan nama Negara China di Indonesia pada era Orde Baru (1967-1998), utamanya sejak Surat Edaran Presidium Kabinet No.6 Tahun 1967 dikeluarkan pasca peristiwa G30/SPKI.
Kata ini juga digunakan untuk menyebut orang2 keturunan Cina (misalnya si A itu keturunan Cina), dan bahasanya (si A bisa berbahasa Cina). Jadi, semua yang berbau Cina dianggap 1, terlepas dari dia sudah WNI atau tidak.
Dari sinilah kemudian muncul anggapan, bahwa orang2 keturunan Tionghoa adalah “warga negara kelas 2”, yang selamanya akan dianggap aseng asing di negeri ini.
Baca juga : G30S/PKI; Apa Efeknya Bagi Tionghoa di Indonesia?
2. Kata “China” (dibaca : Chaina) merupakan penyebutan nama Negara China secara Internasional.
Orang2nya disebut Chinese People (atau Chinese descendant bagi warga keturunan Tiongkok yang ada di luar Indonesia, seperti di Malaysia, Singapore, USA, Australia, dsb), dan bahasanya disebut China Language (di Indonesia disebut bahasa Mandarin, atau bahasa Tionghoa).
Dalam penulisannya, bahasa Mandarin menggunakan aksara Hanzi, dan pelafalannya disebut Pinyin. Bahasa mandarin termasuk 6 bahasa resmi yang digunakan di PBB.
Selain Mandarin, bahasa Kanton (orang2 Guangdong, termasuk Hongkong) dan Hokkian (orang2 Fujian, termasuk Taiwan) merupakan bahasa ke-2 dan ke-3 yang paling banyak digunakan, dimana dalam penulisannya menggunakan aksara Hanzi tradisional yang goresannya lebih kompleks (ver.1949, dan tidak lagi diperbarui).

Kata “mandarin” dalam bahasa Indonesia sendiri diserap bahasa Inggris, yang juga ternyata menyerapnya dari bahasa Portugis yang disebut “mandarim”.
Sumber yang lain menyebutkan bahwa Mandarin secara harfiah berasal dari sebutan orang asing kepada pejabat2 Dinasti Qing, dimana Dinasti Qing (1644-1912) adalah dinasti yang didirikan oleh suku Manchu (dari timur laut Tiongkok), sehingga pejabat2 kekaisaran-nya biasa disebut sebagai Mandaren (滿大人) yang berarti “Pejabat Manchu”.
Bahasa yang digunakan di kalangan pejabat Manchu itu kemudian disebut sebagai “bahasa Mandaren”, dimana penulisannya kemudian berubah menjadi “Mandarin”. Adapun penyebutan bahasa Mandarin yang lain adalah :
• Putonghua (普通话), secara harfiah berarti “ucapan umum”, atau “bahasa yang dimengerti banyak orang”. Istilah ini umumnya digunakan oleh orang Tiongkok daratan.
• Guoyu (国语), secara harfiah berarti “bahasa nasional”, atau “bahasa negara”. Istilah ini umumnya digunakan oleh orang Taiwan.
• Huayu (华语) secara harfiah berarti “bahasa Hua”, atau “bahasa orang2 huaren (华人)”. Istilah ini umumnya digunakan oleh orang2 di Asia Tenggara.
3. Kata “Tionghoa” merupakan penyebutan kepada orang2/komunitasnya, dan budayanya.
Dimana “Tionghoa” berarti orang2 keturunan Tiongkok. Artinya, orang tersebut memiliki pertalian darah dengan Tiongkok, seperti memiliki orang tua, kakek-nenek, atau leluhur yang berasal dari Negara Tiongkok.
Jadi, mereka sudah lahir, besar, bahkan meninggal di Indonesia. Atau WN Tiongkok yang sudah berpindah Kewarganegaraan Indonesia.
So, kaum di luar sana yang suka berteriak2 Antek cina sebaiknya sadar diri. Karena orang Tionghoa di Indonesia secara legalitas dianggap sah sebagai WNI. Apalagi mereka umumnya sudah 2-3 generasi disini.
Bahkan ada yang sudah diatas 7 generasi, jauh sebelum era kolonial Belanda, yang mungkin sudah lebih dulu menghuni bumi nusantara ketimbang leluhur2 ente yang datang belakangan.
4. Kata “Tiongkok” merupakan penyebutan nama Negara China secara resmi di Indonesia.
Kata Tiongkok berasal dari dialek Hokkian (orang2 dari propinsi Fujian dan Taiwan), yang merupakan mayoritas (pendatang) masyarakat Tionghoa di Indonesia, dimana “Tiong” (Hanzi : 中; Pinyin : Zhong) yang berarti “tengah/pusat”, dan “Kok” (Hanzi : 国; Pinyin Guo) yang berarti “negara”.
Dalam penyebutan internasional, Negara Tiongkok disebut China (dibaca : Chaina). Sementara dalam penyebutan bahasa lokal (di negara tersebut) disebut Zhongguo (中国), dan orang2nya disebut Zhongguo ren (中国人) atau Huaren (华人).
Jadi sangat penting bagi pembaca untuk mengetahui perbedaan antara kata “Tionghoa” dan “Tiongkok”. Seperti untuk sejarah, dimana sejarah Tiongkok berarti sejarah yang membahas tentang perdinastian di daratan Tiongkok selama ribuan tahun.
Ini berbeda dengan sejarah Tionghoa, yang membahas tentang perjalanan para perantauan orang2 Tiongkok di Indonesia, terutama di era kolonial hingga masa kino.

B. Organisasi Tiong Hoa Hwee Koan (中华会馆), Perintis Pemakaian Istilah “Tionghoa” di Nusantara!
Di Indonesia, sejarah awal pemakaian kata ‘Tionghoa‘ pada awalnya berasal di lingkup kalangan perkumpulan Tiong Hoa Hwee Koan (中华会馆; Zhonghua Huiguan) atau Rumah Perkumpulan Tionghoa, yang merupakan organisasi yang didirikan oleh beberapa tokoh keturunan Tionghoa di Batavia pada 27 Maret 1900.
Organisasi ini bertujuan untuk mendorong orang2 Tionghoa yang bermukim di wilayah Hindia Belanda agar mengenal jati dirinya sendiri, sehingga mereka bisa bersatu sebagai satu kelompok masyarakat yang dihormati oleh pemerintah Hindia Belanda.
Organisasi yang bergerak di bidang pendidikan inilah yang memprakarsai istilah “Tionghoa” menjadi dikenal secara meluas, lewat sekolah2 yang didirikannya sejak tahun 1900-an. Kegiatan utama THHK yang utama adalah membangun dan membina sekolah2 berbahasa Mandarin, yang berlandaskan pada ajaran Konghucu.
Berdirinya sekolah2 Tiong Hoa Hwee Koan ini merupakan reaksi masyarakat Tionghoa Batavia terhadap pemerintah Belanda, yang tidak pernah memberikan pendidikan kepada anak2 mereka.
Pasca terjadinya peristiwa G30S/PKI, Tiong Hoa Hwee Koan termasuk dalam sekolah2 berbahasa Tionghoa yang ditutup oleh pemerintah Orde Baru dan kepemilikan tanahnya diambil-alih. Sejak saat itu, keluarlah larangan pengajaran dan penerbitan buku2 berbahasa Mandarin.

Baca juga : Perjanjian Dwi Kewarganegaraan Indonesia – Tiongkok (Cina) Tahun 1960-1962
Pada tahun 1920-an, ada kesepakatan antara pers Melayu dan pers Melayu – Tionghoa untuk saling mendukung dan menghormati perbedaan antar etnis, dengan menulis kata “Indonesia” untuk menggantikan kata “Inlander”¹, dan kata “Tionghoa” untuk menggantikan kata “Cina” dalam setiap terbitan halaman korannya masing2.
Intinya, kata wilayah “Hindia Belanda” merujuk pada Indonesia, sementara kata “Cina” merujuk pada Tiongkok.
Ini bagaikan win-win solution bagi kedua etnis dalam mencapai perdamaian, mengingat pada waktu itu pemerintah Belanda menggunakan politik pecah belah (devide et impera) agar masyarakat pribumi dan etnis Tionghoa di Indonesia tidak bersatu.
Sejak saat itulah, perlahan istilah “Cina” atau “Tjina” (ejaan lama) mulai ditinggalkan, karena mengandung arti penghinaan dan bermakna negatif, seperti lemah, kurus, kecil, kotor, budak, buruh, berpendidikan rendah, dan sebagainya. Istilah ini hanya digunakan/diucapkan ketika akan menyerang orang Tionghoa atau orang Tiongkok.
Pada Perang Tiongkok-Jepang (Sino Japanese War) yang meletus tahun 1937 – 1945, istilah “Cina” menjadi sesuatu yang dianggap menghina. Pada waktu itu, pemerintah Jepang menggunakan istilah “Shina” (支那; Zhīnà) yang merujuk pada Negara Tiongkok dalam dokumen2 resmi.
Kata “Shina” sendiri dianggap menghina dan merendahkan oleh pemerintah Tiongkok, sehingga memicu para perantau Tionghoa di Indonesia untuk ikut membenci istilah tersebut.
Pada tahun 1928, Gubernur Jendral Hindia Belanda (1800-an) yang ketika itu menjabat, Andries Cornelies Dirk de Graeff, secara formal mengakui penggunaan istilah “Tionghoa dan Tiongkok” untuk penulisan dokumen2 resmi.

Baca juga : Perjuangan Sekolah Tiong Hoa Hwee Koan di Indonesia
Penggunaan istilah “Tionghoa” ini ternyata hanya bertahan selama 38 tahun (1928-1966), sebelum meletusnya peristiwa G30/SPKI tahun 1965. 2 tahun setelahnya.
Teepatnya pada tanggal 28 Juni 1967, ketua Presidium Kabinet Ampera Soeharto mengeluarkan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor 6 Tahun 1967 untuk menciptakan semangat ANTI CINA di Indonesia.
Hal ini ditidak bisa berjalan tanpa dukungan Kristoforus Sindhunata, yang kala itu menjabat ketua BKPKB (Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa).
Pada Seminar Angkatan Darat ke-2 di Lembang, Jawa Barat tahun 1966, yang membahas masalah keturunan Tionghoa di Indonesia, Sindhunata cs diminta memilih 1 dari 2 istilah : “Cina” atau “Tionghoa“?
Sindhunata akhirnya menganjurkan penggunaan istilah “Cina”. Ia juga mengaku bahwa Ia bersama kelompoknya (para penganjur asimilasi di Indonesia, sewaktu rapat di kantor Gamma/Murbandono Hs) adalah konseptor/perencana dari Inpres 14/1967, yang melarang kebudayaan, adat istiadat, dan tradisi Tionghoa untuk diselenggarakan di tempat terbuka.
Sewaktu pertemuan Siauw Tiong Djien dengan Shindunata di Duarte Inn, Los Angeles, California, yang di fasilitasi oleh CHI (Committee for Human Rights in Indonesia); saat itu pernah diperdebatkan penggunaan istilah “Cina” atau “Tionghoa”.
Ketika itu, suara mayoritas dari peserta seminar memilih istilah Tionghoa, dan hanya 1 orang saja yang berbicara (AD) bahwa dia condong 60% ke istilah “Cina”. Kata2 ini lalu diputar oleh Sindhunata, dan disebarkan di tanah air pada tahun 1966, bahwa di Los Angeles dia memenangkan istilah “Cina” dengan 60% suara.
Sungguh disayangkan, sebenarnya sudah bukan waktunya lagi paradigma pemelintiran sejarah ala ORBA masih dibuat.
Sindhunata juga mengusulkan pelarangan total terhadap perayaan kebudayaan Tionghoa. Namun, Presiden Soeharto kala itu menilai usulan Sindhunata terlalu berlebihan, dan tetap mengizinkan perayaan kebudayaan Tionghoa, namun dilakukan secara tertutup.
Kristoforus Sindhunata sendiri dikenal sebagai seorang Kristiani yang fanatik. Apalagi pada tahun 1960 an terjadi revolusi kebudayaan di Tiongkok, yang salah satu korbannya adalah warga Kristiani di Tiongkok.
Karena itu, terdapat dugaan bahwa segala tindakannya untuk melarang dan menghapuskan tradisi, budaya, adat istiadat, dan bahasa Tionghoa di Indonesia, didasarkan atas rasa balas dendam.
Sebagai akibat dari tindakannya, sekolah2 berbasis Tionghoa pun ditutup oleh pemerintah. Maka, mau tidak mau orang2 Tionghoa akan cenderung menyekolahkan anak2 nya ke sekolah2 swasta berbasis Kristiani.
Ada pula yang berpendapat, bahwa ini merupakan salah satu tujuan dari Kristoforus Sindhunata untuk meng-Kristenkan orang2 Tionghoa di Indonesia pada era Orde Baru.
C. Berikut isi Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No.6 Tahun 1967, yang dapat pembaca lihat disini :

1. Pada waktu kini masih sering … bla … bla … bla
2. Dilihat dari sudut nilai-nilai ethologis-politis dan etimologis-historis, maka istilah “Tionghoa/Tiongkok” … bla … bla … bla … tidak lain hanya mengandung arti nama dari suatu dinasti dari mana ras Cina tersebut datang … bla … bla … bla.
3. Berdasarkan sejarah, maka istilah “Cina”lah yang sesungguhnya memang sejak dahulu dipakai, dan kiranya istilah itu pulalah yang memang dikehendaki untuk dipergunakan oleh umumnya Rakyat Indonesia.
4. Lepas dari aspek emosi dan tujuan politik, maka sudah sewajarnya kalau kita pergunakan pula istilah “Cina” yang sudah dipilih oleh Rakyat Indonesia umumnya.
5. Maka untuk mencapai uniformitas dari efektivitas, begitu pula untuk menghindari dualisme di dalam peristilahan di segenap aparat Pemerintah, baik sipil maupun militer, ditingkat Pusat maupun Daerah kami harap agar istilah “Cina” tetap dipergunakan terus, sedang istilah “Tionghoa/Tiongkok ditinggalkan.
D. Berikut isi surat Keppres No.12 Tahun 2014, yang dapat pembaca lihat disini :
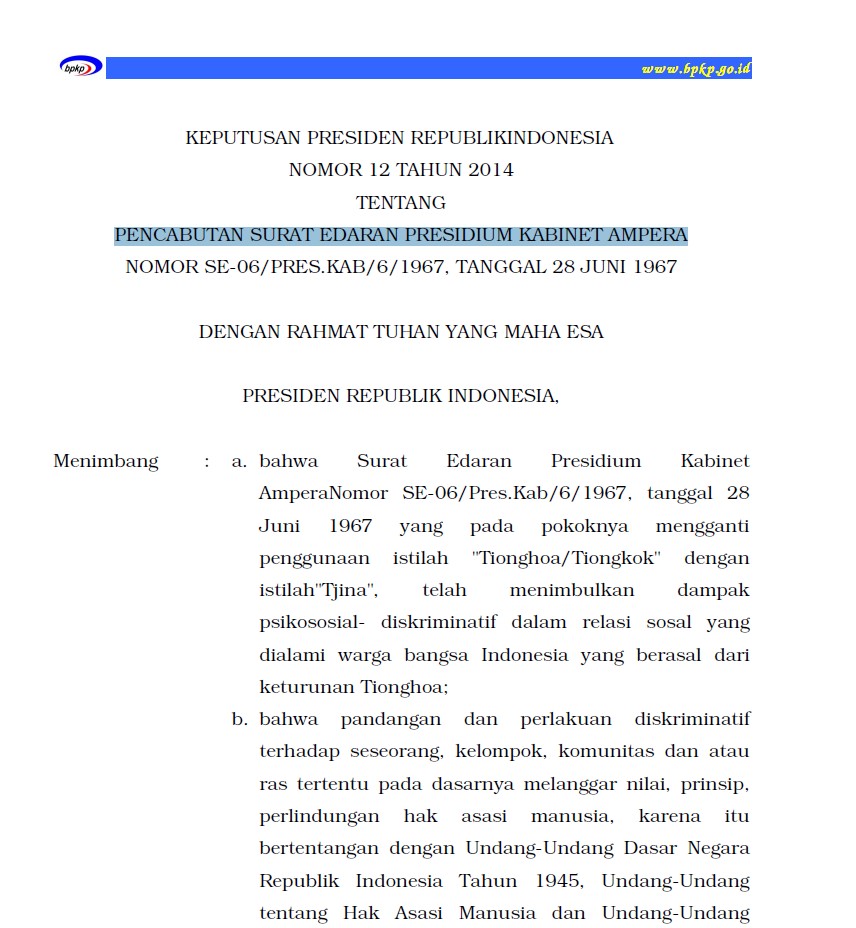
Menimbang :
a. Bahwa Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE-06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967 yang pada pokoknya mengganti penggunaan istilah “Tionghoa/ Tiongkok” dengan istilah “Tjina”, telah menimbulkan dampak psikososial-diskriminatlf dalam relasi sosal yang dialami warga bangsa Indonesia yang berasal dari keturunan Tionghoa;
b. Bahwa pandangan dan perlakuan diskriminatif terhadap seseorang, kelompok, komunitas dan atau ras tertentu pada dasarnya melanggar nilai, prinsip, perlindungan hak asasi manusia, karena itu bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU tentang Hak Asasi Manusia, dan UU tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;
c. Bahwa sehubungan dengan pulihnya hubungan baik dan semakin eratnya hubungan bilateral dengan Tiongkok, maka dipandang perlu untuk memulihkan sebutan yang tepat bagi Negara People’s Republic of China dengan sebutan Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT);
d. Bahwa ketika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan, para perumus UUD tidak menggunakan sebutan Cina, melainkan menggunakan frasa peranakan Tionghoa bagi orang-orang bangsa lain yang dapat menjadi warga negara, apabila kedudukan dan tempat tinggalnya di Indonesia, mengakui Indonesia sebagai tanah aimya, dan bersikap setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana tersurat dalam penjelasan Pasal 26 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
e. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pencabutan Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE- 06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967;
Mengingat : bla … bla … bla.
Memutuskan :
1. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera Nomor SE 06/Pres.Kab/6/1967, tanggal 28 Juni 1967.
2. Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, penggunaan istilah orang dan atau komunitas Tjina/China/Cina diubah menjadi orang dan atau komunitas TIONGHOA, dan untuk penyebutan negara Republik Rakyat China diubah menjadi REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK.
3. Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Catatan¹ : Menurut KBBI, kata/ucapan Inlander merupakan sebuah ejekan bagi penduduk asli di Indonesia oleh orang2 Belanda pada masa penjajahan Belanda; bisa juga berarti “pribumi”, bermental budak (inlander).
Baca juga : Cina Atau Tionghoa? Mana Sebutan yang Benar di Indonesia?